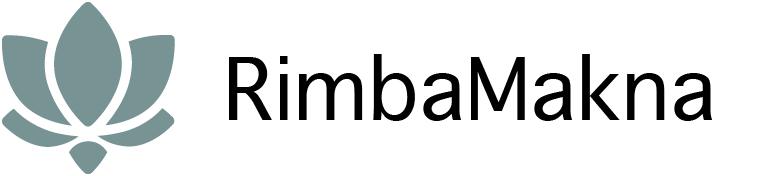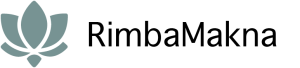
Timer 12:00 — Menatap Akhir Semesta dari Balik Kacamata Hitam.
2,167 words, 11 minutes read time.
Pukulan yang Mengunci
[12:01]
[ARCHIVE//PARTHENON_Δ-LOG 2012X//CLASSIFIED: DIVINE REBELLION]
> Tiga dewa yang saling membenci sepakat pada satu hal: Tuhan
> perlu mati.
>
> Rekaman terakhir sebelum Eye of the Void diaktifkan
>
“Titah The Void adalah ilusi kehendak bebas!”
— Gwaneum
12:11 — Aula yang Terlupakan
Tidak ada catatan resmi tentang apa yang gagal.
Namun seluruh Parthenon berdenyut seperti arsip yang tahu:
sesuatu telah lolos.
Aula Parthenon terasa seperti makam tua
yang menolak menutup dirinya setelah Remisi Resonansi diaktifkan.
Dinding-dinding kristal bergetar lembut,
menyimpan gema ribuan tahun, bercahaya pelan—
seperti napas yang belum diizinkan berhenti.
Udara di dalam ruangan berat:
campuran logam,
debu,
dan sesuatu yang lebih tua dari cahaya itu sendiri.
Akashic Records mengingat.
Parthenon mencatat.
Jika Akashic Records adalah lautan memori,
Parthenon adalah pena yang menuliskan arus di atas permukaannya—
tanpa hak memilih mana yang pantas diingat.
Setiap kata yang diucapkan di sini hidup.
Dan hidup berarti: tidak bisa dihapus.
Cahaya kristal memantul di wajah Agnia.
Mahkotanya berkilau redup—
bukan sebagai tanda kekuasaan,
melainkan sisa keputusan yang tak pernah selesai ditebus.
Di depannya berdiri NiuNiu.
Diam.
Tegang.
Di bawah kulitnya,
resonansi Void masih berdenyut pelan.
Bukan sebagai ancaman,
melainkan sebagai bukti bahwa sesuatu telah menyentuhnya
dan belum sepenuhnya pergi.
Dua sosok yang nyaris sama.
Dipisahkan oleh sejarah.
Disatukan oleh dosa yang tidak pernah diberi bahasa.
Julia dan Delphie berdiri di sisi ruangan,
kaku seperti patung yang mendengar sesuatu
tanpa tahu apakah mereka boleh bereaksi.
Hasan duduk bersila di lantai,
mata terpejam,
mengamati arus resonansi seperti seseorang yang tahu:
apa pun yang datang berikutnya tidak akan meminta izin.
Di sudut ruangan, Sevraya bersandar pada dinding.
Asap rokoknya naik perlahan,
memantul di permukaan kristal,
sementara mata abu mudanya bergerak pelan—
membaca sesuatu yang belum ditulis oleh siapa pun.
12:12 — Tiga Jiwa yang Tak Pernah Padam
Agnia memecah keheningan.
Suaranya dingin. Terukur.
Bukan suara seseorang yang marah,
melainkan suara seseorang yang terbiasa memastikan
bahwa setiap kata akan bertahan setelah ia selesai mengucapkannya.
Namun di balik artikulasi yang rapi itu,
ada yang nyaris tak terdengar menyelip—
ketakutan tipis,
seperti retakan mikro pada kaca structural
yang masih berfungsi, namun tidak lagi utuh.
“Kenapa kau selamatkan dia, Julia?”
Tatapannya tak bergeser.
“Di Dayan. Kau bekerja di bawah kontrakku.
Bayarannya cukup untuk membangun kerajaan sendiri.
Tapi kau memilih menyelamatkannya.”
Ia berhenti. Bukan untuk dramatisasi,
melainkan untuk memastikan
pertanyaan itu tidak punya jalan keluar.
“Kenapa?”
NiuNiu tidak membuka mulut.
Jawaban muncul dalam bentuk gerakan.
Pisau Andamante melesat—
tipis,
dingin,
tanpa jeda antara niat dan tindakan.
Udara terbelah sebelum siapa pun
sempat menamai apa yang sedang terjadi.
Agnia bergerak setengah denyut terlambat—
dan itu cukup. Pisau dari sarungnya terangkat.
Dua bilah bertemu.
Denting logam memecah kristal Parthenon.
Serpihan cahaya jatuh,
seperti ingatan yang terlepas dari tempatnya disimpan.
Cahaya ruangan berkedip.
Parthenon menonton.
Tinju NiuNiu menghantam rahang Agnia.
Bunyinya tajam—
bukan sekadar benturan,
melainkan nada pertama dari simfoni berbahaya
yang telah lama ditunda oleh sejarah mereka.
Agnia tersentak mundur.
Darah tipis di bibirnya berkilau.
Ia tidak jatuh.
Tendangannya menghantam perut NiuNiu,
mengirim kembarnya dua langkah ke belakang.
“Kau terlalu lemah,” desis Agnia.
NiuNiu mengangkat wajahnya.
Mata hitam itu tidak menuntut simpati.
Ia hanya membawa luka yang sudah terlalu lama hidup tanpa saksi.
> “Kau iri,”ketik NiuNiu pelan.
> “Sora memilihku.”Pukulannya menghantam dada Agnia.
Lantai Parthenon bergetar.
“Sora mati karena kau,” balas Agnia—
dingin, nyaris administratif.
“Karena kau tidak menariknya keluar dari Dayan.”
Darah bercampur di lantai kristal.
Napas mereka pecah.
Cahaya di dinding berubah warna,
berkedip seperti kilat yang terperangkap di dalam bahan padat.
Dan saat kekerasan itu hampir berubah menjadi kebisingan—
Sevraya melangkah masuk.
Pelan.
Tenang.
Namun dunia bereaksi lebih cepat daripada manusia.
Sesuatu terdengar—
bukan suara,
melainkan tekanan.
Rendah.
Dalam.
Frekuensi yang tidak melewati udara atau mesin,
melainkan langsung menekan tulang,
seperti memanggil sesuatu yang telah lama disimpan oleh tubuh itu sendiri.
Parthenon bergetar halus,
seperti ingatan lama yang dipanggil kembali tanpa izin.
Julia menegang.
Delphie menunduk.
Agnia dan NiuNiu—
dua api yang saling membakar—
membeku di tempatnya.
Karena hanya satu kondisi yang mampu memunculkan frekuensi itu:
Sinkronisasi 0.00001 hertz.
Resonansi yang tidak pernah stabil di bawah mediasi mesin.
Resonansi yang dulu dianggap kesalahan.
Eksperimen.
Kebetulan.
Sevraya berdiri di antara dua api itu.
Ia meletakkan tangannya pada bilah Andamante
yang nyaris menembus leher Agnia.
“Cukup,” katanya pelan.
Pelan—
namun frekuensi itu merespons.
Menguat.
Gelombang hening menyapu aula.
Cahaya di dinding bergeser.
Huruf-huruf kuno muncul sekejap,
lalu lenyap,
seperti sistem yang baru saja mengingat sesuatu lalu memilih diam.
Parthenon mencatat.
Bukan sebagai konflik.
Bukan sebagai pelanggaran.
Melainkan sebagai kondisi.
Tiga entitas yang seharusnya tidak pernah sinkron berdiri terlalu dekat.
> Void-born.
> Didymoi.
> Hydrochoos.Dan seperti pertama kali mereka berdiri bersama—
tanpa tahu apa artinya—
mereka stabil.
Sinkron.
Berbahaya.
12:13 — Tiga Dewa, Satu Luka
Sevraya menatap mereka berdua.
“Kalian tidak pernah berubah,” katanya pelan.
“Dunia sudah berganti,
tapi amarah kalian masih tinggal tepat di tempat yang sama.”
NiuNiu tidak menjawab.
Matanya memantulkan wajah Sevraya—
bukan manusia, melainkan ombak gelap yang terus menggulung,
mencari bentuk yang tak pernah diizinkan selesai.
“Kalian masih memainkan naskah lama,”
lanjut Sevraya. “Agnia si ratu. NiuNiu si korban.”
Agnia tersenyum getir.
“Dan kau?” balasnya.
“Penulis naskah itu?
Atau pengkhianat hidup yang selalu berpura-pura jadi penengah?”
Sevraya membalas dengan senyum dingin—
senyum yang tidak pernah mencapai mata.
“Aku cuma tinta,” katanya.
“Parthenon yang menulis. Bukan aku.”
Delphie menatapnya, bingung namun terpikat.
“Parthenon… mencatat?”
Sevraya mengangguk kecil.
“Akashic Records menyimpan semua yang pernah ada.
Tapi Parthenon menulis ulang hal-hal yang seharusnya tidak pernah ada.
Setiap darah yang jatuh di sini”—
ia menyentuh dinding kristal yang bergetar halus—
“menjadi kalimat baru dalam sejarah semesta.”
Hasan berbicara tanpa membuka mata,
seperti menjawab sesuatu yang hanya ia sendiri yang dengar.
“Dan sejarah,” katanya tenang,
“tidak pernah menulis dengan tinta.
Ia menulis dengan darah— dan rasa bersalah.”
12:14 — Luka yang Tidak Sembuh
Agnia melangkah maju.
Cahayanya memantul di dinding kristal,
seolah memastikan setiap kata
memiliki tempat di arsip yang tidak memaafkan.
“Kau kira aku tidak tahu apa yang kau lakukan di Aeonexus?”
Nada suaranya datar.
Ketajamannya datang belakangan.
“Mereka menyebutmu tawanan.
Tapi semua orang tahu—
kaulah yang memerintah planet itu.”
Sevraya tidak mundur.
Ia hanya mengangkat dagu setengah denyut—
gestur kecil yang terasa seperti peringatan,
bukan pembelaan.
“Tawanan, ratu, penguasa—
semuanya nama lain dari kendali,”
ujar Sevraya pelan.
“Bedanya, aku sadar
siapa yang mengikatku.”
Agnia menyipitkan mata.
“Sora?”
Senyum Sevraya pecah perlahan—
pahit, indah, dan tidak meminta simpati.
“Sora,” katanya,
“adalah satu-satunya makhluk
yang membuatku lupa
betapa melelahkannya menjadi dewa.”
Hening.
Bukan hening kosong.
Hening yang menggigit,
seperti luka yang disentuh tanpa izin.
NiuNiu menunduk.
Jarinya bergerak di gelang hologram—
karena kata lisan
terlalu mudah dipelintir menjadi pembenaran.
Tulisan itu muncul di udara, dingin dan rapi:
> “Kau cuma ingin tahu
rasanya punya jantung
yang masih berdebar.”Agnia menoleh ke arahnya.
Ada kemarahan di sana.
Ada juga sesuatu yang lebih rapuh.
“Dan kau, Niu,” katanya pelan,
“kau iri?”
NiuNiu menatapnya lama.
Lalu jarinya bergerak lagi—
cepat, presisi,
seperti belati yang tidak ragu memilih sasaran:
> “Aku muak melihat masa lalu
dijadikan alasan
untuk terus hidup
di masa kini.”Kata-kata itu jatuh
seperti pecahan kaca
di lantai kristal Parthenon.
Hening.
Namun kali ini,
tidak ada yang bisa berpura-pura
tidak terluka.
Agnia menunduk setengah inci—
bukan tanda menyerah,
melainkan pengakuan yang terlalu lama ditunda.
Sevraya memejamkan mata.
Seolah kalimat itu
membuka pintu lama
yang pernah mereka kunci Bersama
dan sepakat untuk tidak pernah membukanya lagi.
Parthenon bergetar halus.
Kristalnya merespons—
mencatat luka itu
tanpa menawarkan jalan keluar.
12:15 — Tusukan yang Menyatukan
Hening.
Bukan hening yang damai,
melainkan jeda
seperti waktu yang ragu
apakah ia masih berhak bergerak.
NiuNiu bergerak pertama.
Bukan karena amarah—
melainkan karena sesuatu di dalam dirinya
menjawab panggilan
yang lebih tua dari tubuh,
lebih tua dari pilihan.
Andamante menyambar udara.
Sevraya tidak menghindar.
Ia mengangkat telapak tangannya
dan menerima bilah itu
seperti menerima konsekuensi
yang telah lama tertunda.
Darah jatuh.
Satu tetes.
Lalu satu lagi.
Lantai kristal bereaksi
sebelum siapa pun sempat bernapas.
Cahaya biru tua merembes dari bawah,
menyebar ke seluruh aula,
seperti jantung purba
yang dipaksa bangun
tanpa izin.
Agnia tertegun.
“Sevraya—”
Kalimat itu tidak pernah selesai.
NiuNiu sudah memutar tubuh,
menarik napas kecil
yang nyaris tak terdengar,
lalu menusukkan Andamante
ke tangan Agnia.
Agnia menahan erangan.
Darahnya jatuh
ke segel yang sama.
Kristal bergetar—
bukan menolak,
melainkan membuka diri.
Agnia menarik napas.
Marah dan pasrah
bertemu di satu garis tipis
yang tidak lagi bisa ditarik ulang.
“Kau gila, Niu,” bisiknya.
“Segel itu—”
Terlambat.
NiuNiu memutar gagang Andamante
dan, tanpa ragu,
menekan tubuhnya sendiri ke atas bilah itu.
Tusukan terakhir.
Darah NiuNiu jatuh.
Titik penutup.
Segel menyala penuh.
Tiga warna bercampur:
merah Agnia,
biru Sevraya,
hitam NiuNiu.
Parthenon bergetar
seperti makhluk
yang baru sadar
ia telah terlibat.
Tulisan kuno muncul,
berputar dalam pola
yang tidak meminta untuk dibaca.
Segel itu hidup.
Sevraya tersenyum tipis
di balik rasa sakit
yang tidak ia tolak.
“Sekarang,” katanya pelan,
“kita bertiga terikat kembali.”
Cahaya biru tua memucat,
menjadi cahaya bening
tanpa pusat.
Frekuensi rendah muncul—
bukan di udara,
melainkan di dalam tulang.
hmmmmmmmmmmmm
Agnia memejamkan mata.
Getaran itu masuk ke nadinya
tanpa bertanya.
Sevraya merasakannya
di balik tulang pipinya—
seperti ingatan
yang tidak bisa dihapus.
NiuNiu merasakannya paling jelas.
Gelombang itu berbicara
dengan bahasa The Void.
> 0.00001 hertz.Tiga luka
menjadi satu frekuensi.
Dan setelah segel mengunci,
jarak tidak lagi menjadi syarat.
Mereka merasakannya
meski berdiri
di ujung dunia yang berbeda.
Julia terhuyung satu langkah.
Napasnya terseret
keluar dari dadanya.
Rasa logam terasa di lidah.
Delphie menggenggam kursinya.
“A-aku… merasakannya…”
Hasan membuka mata.
Gelombang itu menyentuhnya
seperti nama
yang disebut dari tempat
yang terlalu jauh
untuk diabaikan.
“Frekuensinya masuk,” katanya pelan.
“Ke The Merge.”
Didalam Dorian Grey artefak The Void bergetar
menyambut kehadiran resonansi baru.
Trinitas pertama—
Agnia.
Sevraya.
NiuNiu.
Menjadi Frekuensi 0.00001.
Trinitas kedua—
Julia.
Delphie.
Hasan.
Menjadi The Merge.
Dan sejak detik itu,
tidak ada satu pun dari mereka
yang bisa berpura-pura
bahwa jalan ini masih bisa dibelokkan.
Karena tujuan itu
tidak lagi dipilih.
The Merge: mengunci Tuhan yang tersesat.
0.00001: membunuh Tuhan yang salah.
Artefak The Void menyeimbangkan keduanya.
12:06 — Pakta Para Dewa
Untuk pertama kalinya,
Julia menatap mereka bertiga tanpa mencoba memahami.
Dan di momen itu,
ia menyadari satu hal
yang menghantam lebih keras daripada perang mana pun:
tidak ada yang adil di dunia ini.
Tidak pernah.
Cahaya Parthenon memantul di tubuh mereka—
bukan seperti cahaya yang menerangi,
melainkan seperti cahaya yang menilai.
Menimbang
tiga versi berbeda dari satu hal yang sama:
Kegilaan
yang lahir dari luka
dan dipelihara oleh kekuasaan.
Agnia.
Tubuhnya masih tegak,
namun kelelahan tidak lagi bersembunyi.
Bahu sedikit turun.
Tangan kanan gemetar halus
saat menggenggam bilah senjata.
Garis-garis di wajahnya
bukan sekadar usia,
melainkan peta dari semua malam
ketika ia harus memilih sendirian
di takhta
yang selalu menuntut lebih
daripada yang bisa diberikan manusia mana pun.
Ia hidup.
Begitu hidup.
Dengan denyut yang tidak bisa dipalsukan,
dan beban yang tidak bisa dibagi.
Sevraya.
Wajahnya nyaris sempurna—
terlalu sempurna
untuk menyimpan cerita.
Rambutnya bergelombang seperti laut
yang telah lama berhenti mengenal pantai.
Tubuhnya tegak,
gerakannya presisi,
seolah dirinya dikendalikan
dari jarak yang aman.
Mata abu mudanya jernih.
Namun kosong.
Ia tidak hidup.
Ia berfungsi.
NiuNiu.
Tubuh lima belas tahun.
Kulit tanpa garis waktu.
Rambut hitam pendek,
poni menutup mata.
Ia seharusnya mengeluh soal PR,
bukan berdiri
di tempat
di mana Tuhan pun bisa mati.
Namun matanya terlalu tua.
Pupil hitam itu menyimpan dekade kehancuran
yang tidak pernah diminta
oleh tubuh sekecil itu.
Tangannya penuh bekas luka—
tangan yang belajar membunuh
sebelum sempat belajar
menulis surat cinta.
Ia tidak berdiri seperti anak.
Ia berdiri seperti prajurit
yang tidak pernah diberi masa kecil
untuk disesali.
Tiga ratu.
Bukan karena mahkota,
melainkan karena tidak ada siapa pun
yang bisa menggantikan posisi mereka.
Satu generasi tiga patahan
yang seharusnya saling melengkapi.
Tiga cara berbeda
dalam gerakan.
Julia memandangi mereka lama.
Dunia terasa terlalu senyap,
seolah semesta menahan napasnya sendiri.
Ia manusia biasa.
Tubuhnya punya batas.
Hatinya punya ketakutan.
Pikirannya masih percaya
pada hal-hal sederhana—
makan pagi,
cinta,
dan hukuman yang adil.
Namun yang berdiri di hadapannya
bukan pahlawan.
Melainkan
tiga dewa
yang membuat pakta
untuk membunuh Tuhan.
Absurd.
Tidak masuk akal.
Tidak seharusnya mungkin.
Namun itu terjadi.
Tepat di depan matanya.
Dan di dalam hatinya,
Julia tahu:
mereka tidak hanya akan membunuh Tuhan.
Tapi mereka telah membunuh
satu sama lain—
perlahan,
potongan demi potongan—
selama puluhan tahun.
Ia merinding.
Memeluk Delphie.
Bukan karena takut
pada Tuhan yang akan mati—
melainkan pada tiga perempuan
yang akan hidup
setelahnya.
Unholy Trinity.
Algojo tanpa altar.
> ~finalize(UNHOLY_TRINITY.pact)
>
> bind FREQUENCY::0.00001_hz to:
> Agnia.light -> crown of the dying empire
> Sevraya.sea -> echo of drowned gods
> NiuNiu.shadow -> blade never sheathed
>
> bind THE_MERGE.protocol to:
> Julia.rose -> witness who cannot unsee
> Delphie.rose -> architect of broken systems
> Hasan.air -> the breath between wars
>
> TARGET: Zero.0 (false god)
> METHOD: synchronized deicide
> ARCHIVE: PARTHENON.bloodlog
> OBSERVER: AKASHIC.eternal
>
> if (GOD.terminated == TRUE):
> universe.vacancy = INFINITE
> echo "throne unmade, crown unclaimed"
>
> AUTHOR: ∴UNKNOWN∴
> STATUS: IRREVERSIBLE
> NEXT: UNKNOWN
>
> ~seal(Ø)Akhir dari Timer 12:00
問
Jika yang mendengarkan tidak pernah berbicara,
siapa sebenarnya
yang sedang diuji?
Share/Copy link: